Doea Tanda Tjinta Persembahan Pentas Indonesia Kita
- Hafidh Nashrullah
- Aug 5, 2016
- 2 min read
Updated: Aug 8, 2023
Artikel: Isthi Rahayu | Foto: Hafidh Nasrullah

Tak seberapa lama waktu bergeser dari pukul 20.00 WIB, lampu diGraha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, dipadamkan yang disusul dengan mengalunnya suara emas Endah Laras, penyanyi keroncong asal Sukoharjo, Jawa Tengah. Wanita berperawakan besar dengan sanggul dan berbusana kebaya ini melantunkan tembang yang tak asing lagi di telinga para penonton: La Vie en Rose. Namun ada yang berbeda dengan lagu asal Perancis yang dipopulerkan oleh Édith Piaf pada tahun 1945 itu, selain dinyanyikan dalam versi bahasa Inggris, La Vie en Rose yang mengalun pada malam tersebut pun diaransemen ulang dalam kemasan musik keroncong.
Malam itu, 29 Juli 2016, Redaksi Seputar Event berkesempatan untuk menyaksikan Pentas Indonesia Kita produksi ke-20 yang mengambil tema warisan musikal keroncong untuk dipersembahkan kepada masyarakat yang diberi tajuk Doea Tanda Tjinta. Sesuai dengan temanya maka selama kurang lebih tiga jam para penonton yang memenuhi GBB pun dihibur dengan beagam lagu keroncong kenamaan yang diaransemen dengan gaya terbaru dan berpadu apik dengan genre musik lainnya seperti blues, rock, hingga etnik. Guna mendukung tema tersebut, sederet musisi keroncong dan seriosa malam itu dihadirkan, yaitu Endah Laras, maestro keroncong asal Kota Gede: Subardjo HS, dan penyanyi seriosa Heny Janawati.
Bukan Pentas Indonesia Kita namanya apabila tema yang disajikan dikemas secara “biasa-biasa” saja. Seperti produksi-produksi terdahulu, malam itu para penonton pun disuguhi drama musikal yang dipenuhi guyonan segar oleh sederet komedian, sebut saja Cak Lontong, Akbar, Merlyn Sopjan, Trio Gam, Marwoto, Susilo Nugroho, dan Olga Lidya.
Doea Tanda Tjinta berlatar zaman pergerakan kemerdekaan, yang juga merupakan saat-saat di mana musik keroncong sedang populer di kota Batavia dan beberapa kota besar lainnya. Saat-saat di mana para pemuda-pelajar pada saat itu mulai menyemai benih pemikiran tentang kemerdekaan yang tak ayal telah menjadi ancaman tersendiri bagi pemerintah Hindia Belanda.
Kendati merupakan topik yang cukup berat, namun Cak Lontong (Lontong van der Cak) dan kawan-kawan berhasil membawakan topik ini menjadi sajian yang ringan, mengocok perut, namun “mengena.” Dibumbui dengan kisah perebutan cinta antara Lontong van der Cak yang merupakan pemuda keturunan Belanda dengan sang ayah yang berusaha memenangkan hati Noni (Olga Lidya), selama kurang lebih tiga jam para penonton dihibur dengan aksi para pelakon yang berpadu apik dengan penampilan Endah Laras, Subardjo HS, dan Heny Janawati.
Tampaknya rasa cinta Lontong van der Cak pada Noni bukannya tanpa maksud. Ia berusaha untuk memengaruhi para pemuda, termasuk Noni, dan membujuk mereka agar terus mendukung pemerintahan Hindia Belanda. Namun—kendati merupakan keturunan Tionghoa—Noni tetap berusaha mempertahankan keyakinan dan prinsipnya untuk lebih mendukung pergerakan Indonesia. Hingga di akhir cerita, Noni pun menerima sebuah warisan dari nenek moyang berupa sebuah jam yang sudah menemani leluhur Noni melawan penjajah di masanya. Hal ini semakin memantapkan hatinya untuk tetap membela bangsa yang menjadi tempatnya bernaung saat ini: Indonesia.
Walau dibalut sebagai drama komedi musikal, namun melalui pertunjukan ini—selain ingin mengakrabkan keroncong di hati dan telinga anak muda Indonesia—Pentas Indonesia Kita ingin mengingatkan masyarakat Indonesia bahwa kemerdekaan bangsa ini bukan hanya hasil perjuangan dari satu suku belaka. Bukan hanya Jong Java, Jong Sumatera, atau Jong Celebes semata. Namun ada andil dari pergerakan pemuda lainnya dari seluruh Indonesia, termasuk pemuda keturunan... dalam hal ini Tionghoa.








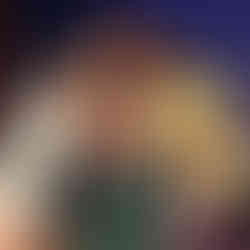





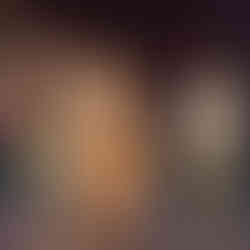

































留言